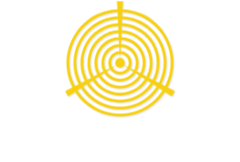Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih, maka bagi mereka karunia yang tiada putus-putusnya. – Q.S. At-Tiin [95]: 4-6
AL-QUR’AN menggambarkan manusia sebagai makhluk yang menempati kedudukan yang sangat tinggi dan sangat khusus. Allah SWT, Sang Raja Semesta itu "mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 31) dan memintanya mengajarkan kembali rahasia-rahasia itu kepada makhluk-makhluk lainnya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 33). Allah bahkan menyuruh kepada para Malaikat agar bersujud kepada Adam (Q.S. Al-Baqarah [2]: 34).
Namun dalam pandangan beberapa filsuf, eksistensi manusia hanyalah sebuah kebetulan alamiah saja. Hidup dalam pandangan mereka hanyalah sebuah rutinitas untuk mengukur jalanan dari pagi sampai petang, mencari makan, mengisi lambung yang tak seberapa ini.
Allah menantang pemikiran-pemikiran ini dalam firman-firman-Nya. Salah satunya berbunyi:
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakanmu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? – Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 115
Allah sungguh tidak main-main dengan penciptaan manusia. Kedudukan khusus yang disematkan-Nya kepada makhluk yang satu ini diiringi pula oleh sekian ragam "fasilitas" yang juga khusus, sangat kaya dan kompleks. Tidakkah kita merasakannya? Saat menyusuri tempat-tempat di hamparan, gunung-gunung dan lautan, segala hal di dalamnya tampak begitu "ramah" kepada kita, "Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya?" (Q.S. Hajj [22]: 65)
Allah bahkan secara khusus mendesain matahari dan bulan yang beredar sedemikian rupa demi mendukung satu kebutuhan manusia yang esensial akan bilangan dan perhitungan (Q.S. Yunus [10]: 5).

Allah sungguh tidak main-main dengan penciptaan manusia. Kedudukan khusus yang disematkan-Nya kepada makhluk yang satu ini diiringi pula oleh sekian ragam "fasilitas" yang juga khusus, sangat kaya dan kompleks. Tidakkah kita merasakannya?
Bola-bola gas super raksasa yang bersinar terang di langit, terwujud dalam konstelasi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dengan sekian pelik hukum fisikanya adalah "…agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut" (Q.S. Al-An’aam [6]: 97). Lalu kini kita berdiri di atas sebintik debu bernama Bumi ini di tengah kemahaluasan Semesta Raya yang semuanya—ya, seluruhnya!—telah ditundukkan-Nya bagi kita manusia.
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami-(nya). – Q.S. An-Nahl [16]: 12
Tidakkah semua perlakuan khusus itu memicu pertanyaan di dalam diri kita, siapakah sebenarnya makhluk ini? Siapakah kita? Dari mana asalnya, kemana, dan untuk apa kita ada di sini?
Apakah kita menganggap bahwa hidup hanya berawal di sini dan di sini pula hidup itu berakhir? Pernahkah kita membayangkan di sebuah rentang waktu, jauh sebelum kita terlahir di dunia, kita pernah bercakap-cakap dengan Dia yang kita sebut "Tuhan", Sang Raja Semesta Raya itu?

Apakah kita menganggap bahwa hidup hanya berawal di sini dan di sini pula hidup itu berakhir? Pernahkah kita membayangkan di sebuah rentang waktu, jauh sebelum kita terlahir di dunia, kita pernah bercakap-cakap dengan Dia yang kita sebut "Tuhan", Sang Raja Semesta Raya itu?
Manusia adalah Saksi Allah
Al-Qur’an merekam sebuah jejak sejarah dari masing-masing kita, keturunan Adam (Bani Adam), tentang sebuah peristiwa di sebuah alam yang disebut oleh para ulama sebagai Alam Alastu atau Alam Persaksian:
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). – Q.S. Al-A'raaf [7]: 172
Ayat ini adalah sebuah reportase penting tentang suatu masa ketika kita sungguh berhadap-hadapan dengan sosok Sang Raja Diraja Semesta itu. Saat itu diambil sebuah kesaksian terhadap tiap-tiap diri (nafs/jiwa), masing-masing kita: "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Dan kita pun menjawab: "Betul, kami menjadi saksi."
"Saksi", atau "syuhada" dalam bahasa Arab, secara umum merujuk kepada pihak yang dihadirkan karena dianggap memiliki pengetahuan tentang suatu hal atau karena ia menyaksikan kejadian tertentu. Dalam hal ini, manusia dinisbatkan sebagai saksi Allah, Tuhan Semesta Alam.
Manusia adalah saksi yang disumpah untuk memberikan keterangan yang membenarkan-Nya. Manusialah yang akan angkat bicara atas setiap keraguan tentang keberadaan-Nya, tentang keesaan-Nya, tentang kebesaran-Nya, tentang ke-99 asma-Nya. Kita menjadi saksi atas itu. Karena bukankah kita telah berhadap-hadapan dengan Sang Maha Agung, bercakap-cakap dan menyaksikan-Nya?
Dalam konteks yang lain, syahid atau syuhada (bentuk jamak dari syahid) kerap diartikan sebagai orang yang mati syahid di medan perang—yang di dalam Al-Qur’an disebutkan sebagai salah satu di antara orang-orang yang dianugerahi nikmat (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 69) selain para Nabi, Shiddiqin, dan Shalihin.
Namun makna asali dari kata ini sebenarnya adalah "ia yang bersaksi" dan tidak ada kaitannya dengan sebuah peperangan. Syahid merupakan sebuah "gelar" orang-orang yang teguh berdiri dalam kesaksiannya, yang tidak selamanya sebagai martir dalam peperangan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Siapa yang berdoa kepada Allah dengan benar untuk mendapatkan mati syahid, maka Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidur" (H.R. Muslim). Juga, di hadits yang lain disebutkan,"Sebagian besar para syuhada dari umatku adalah mereka yang mati di tempat tidur" (H.R. Ibnu Mas’ud).
Oleh karena itu, ungkapan yang lebih tepat dalam menggambarkan arti syahid atau syuhada adalah ia yang memegang teguh kesaksian Allah atas penciptaan-Nya, kasih dan sayang-Nya, keagungan-Nya, penggelaran seluruh takdir dan asma-asma-Nya, fitrah-Nya. Ia menjadi tonggak kesaksian Tuhannya itu bahkan ketika hidup sampai di ujung maut sekalipun. Maka, barangkali dalam konteks inilah kita memahami sabda Rasulullah SAW bahwa "Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati terkena wabah adalah syahid, dan seorang Ibu yang meninggal karena melahirkan anaknya adalah syahid, maka anaknya menariknya dengan tali pusar untuk masuk ke surga" (H.R. Ahmad).
Itulah prinsip dasar kebersaksian atas Allah Ta’ala, peran yang diemban tiap-tiap diri umat manusia.

Arti syahid atau syuhada adalah ia yang memegang teguh kesaksian Allah atas penciptaan-Nya, kasih dan sayang-Nya, keagungan-Nya, penggelaran seluruh takdir dan asma-asma-Nya, fitrah-Nya.
Abdi Allah: Sang Ksatria Raja
Terdapat beberapa petunjuk lain di dalam Al-Qur’an yang bisa menuntun kita kepada indikasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar dan maha penting tentang eksistensi manusia.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. – Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 56
Ini adalah ayat yang sangat populer dan sungguh dalam maknanya. Kata ya’buduun di akhir ayat tersebut memang tak jarang diterjemahkan sebagai "beribadah kepada-Ku", namun kata tersebut memiliki arti inti yang lebih fundamental, yakni "mengabdi kepada-Ku" atau "menjadi abdi-Ku": suatu indikasi tentang sebuah peran yang disematkan baik kepada penciptaan jin maupun manusia.
Ayat tersebut menginformasikan bahwa manusia adalah sesosok makhluk yang diciptakan untuk menjadi abdi, dan bukan sembarang abdi: ia mengemban tugas dan misi suci dari Allah Rabb Al-Alamin.
Kita dapat merasakan sebuah redaksi penunjukan langsung di ayat tersebut: Allah Ta’ala mengatakan "abdi-Ku", bukan "abdi Kami" atau abdi siapa-siapa—manusia, dalam ayat tadi adalah jelas “milik-Ku”. Manusia tidak membawa tugas kepelayanan tingkat dua atau tiga dari malaikat tertentu atau jin tertentu atau makhluk-makhluk lainnya. Manusia mengemban tugas suci langsung dari Allah Ta’ala, Sang Raja Diraja Semesta itu sendiri. Bila diibaratkan, manusia adalah para ksatria Raja, pelayan raja atau menteri dan abdi negara yang bertanggung jawab langsung kepada pucuk pimpinan tertingginya.
Masing-masing dari kita semua membawa misi suci dari Allah Ta’ala, tak satu pun terkecuali. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa "Tiap-tiap diri bekerja sesuai dengan untuk apa dia diciptakan, atau menurut apa yang dimudahkan kepadanya." (H.R. Bukhari)
Tapi pernahkah kita merenungkan barang sejenak, di manakah kini para abdi Allah yang mulia itu? Bila kita manusia, jajaran para ksatria itu, apakah kita telah "lupa kepada kejadiannya; dan (malah) berkata: 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?'" (Q.S. Yaasiin [36]: 78). Apakah kita telah terjerumus ke dalam ke limbah nista dan nestapa, terbata-bata dalam kehidupan, lupa akan siapa dirinya dan tak tahu arah mana yang dituju? Adakah itu lantaran telah tertutup telinga, mata dan hati, hingga kita berperilaku "seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi?" (Q.S. Al-A’raaf [7]: 179).
Namun terlepas dari semua "pembangkangan" itu, kita paham satu hal: bahwa ada sesuatu yang agung pada penciptaan manusia, masing-masing kita. Manusia, pada hakikatnya, adalah para saksi Allah, saksi atas kemaha-agungan-Nya, yang menjadi abdi-Nya, pelayan-Nya, ksatria-Nya dalam mengemban suatu tugas atau misi suci tertentu dari Allah Ta’ala.
Khalifah di Muka Bumi
Ayat Al-Qur’an berikut ini menjelaskan lebih jauh seperti apa tugas atau misi yang diemban oleh kita manusia—sebuah peran yang tidak dinisbatkan kepada malaikat, jin atau makhluk-makhluk lainnya.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” – Q.S. Al-Baqarah [2]: 30
Di ayat tersebut, Allah menyebutkan di hadapan para Malaikat-Nya tentang kepada siapa Dia embankan tugas atau misi kekhalifahan di muka bumi ini, yakni kepada Manusia.
Istilah khalifah di dalam bahasa Arab berarti "pemimpin", atau "wakil" atau "pengganti"—yakni ia yang mewakili atau menggantikan suatu otoritas kepemimpinan tertentu, seperti halnya duta besar yang mewakili kepala pemerintahan suatu negara di luar negeri. Maka di sini, sebagai contoh, kita mengenal Khulafaur-Rasyidin, yang mengandung kata khulafa (jamak dari kata khalifa), yakni mereka yang menggantikan atau mewakili Rasulullah SAW sepeninggal Beliau sebagai pemimpin umat Islam.
Maka,"khalifah di muka bumi" pada ayat tersebut mengandung arti "pemimpin atau wakil Allah di muka bumi". Makna ini secara khusus tersirat pula di dalam sebuah ayat yang lain:
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. – Q.S. Shaad [38]: 26
Mari kita renungkan baik-baik ayat yang sangat penting ini.
Mengapa Allah memerintahkan Nabi Daud a.s. agar "berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil" padahal bukankah Allah menyandang gelar Al-Hakim (salah satu dari 99 Asma al-Husna) dan Dia telah menyebut diri-Nya sebagai "yang memberi keputusan dan Hakim yang sebaik-baiknya"? (Q.S. Yunus [10]: 109). Jawabnya tentu, karena Allah telah "menjadikan khalifah"—dalam arti "mewakilkan suatu urusan" di muka bumi kepada manusia. Allah telah mewakilkan urusan kehakiman, urusan pemberian keputusan secara adil di kalangan Bani Israil kala itu kepada Nabi Daud a.s.
Maka demikianlah, ketika menjadikan khalifah di muka bumi itu, Allah mewakilkan atau mengamanahkan suatu urusan kepada wakil pengganti (khalifah) tersebut—dan itulah yang menjadi tugas atau misi spesifik yang diemban oleh seorang manusia sebagai khalifah.
Perhatikan bahwa tak hanya kepada Daud a.s., Allah pun menjadikan Musa a.s. sebagai khalifah bagi kaumnya di masa itu. Allah mewakilkan kepada tiap-tiap nabi masing-masing urusannya, termasuk kepada Rasulullah SAW sebagai manusia teragung, segel atau penutup kenabian (khatamun nabiyyin), dan uswatun hasanah, teladan terbaik bagi umat manusia.
Tiap-tiap diri kita adalah sebuah "instrumen" yang mewakili suatu urusan ('amr) yang spesifik—di sebuah ruang waktu tertentu, atau situasi tertentu—sebagai perwujudan rancangan Allah menjadikan para wakil-Nya di muka bumi ini. Maka, sebagaimana Allah telah mewakilkan aspek Al-Hakim kepada Daud a.s., kepada masing-masing diri kita pun Allah telah sematkan—dalam kadar tertentu—beberapa khazanah dari asma-asma-Nya itu, fitrah-Nya, untuk mendukung urusan kekhalifahan tersebut. "(Demikianlah) Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut Fitrah itu." (Q.S. Ar-Ruum [30]: 30), sebagaimana pula Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan citra-Nya." (H.R. Bukhari, Muslim)

Tiap-tiap diri kita adalah sebuah "instrumen" yang mewakili suatu urusan ('amr) yang spesifik – di sebuah ruang waktu tertentu, atau situasi tertentu--sebagai perwujudan rancangan Allah menjadikan para wakil-Nya di muka bumi ini.
Maka tidakkah kita memiliki rasa itu, menyadari bahwa tiap-tiap diri kita memiliki kompetensi yang berbeda-beda, kekuatan dan kekurangan, bidang-bidang yang mudah dikuasai dan bidang-bidang yang sulit? Masing-masing kita disematkan suatu "konfigurasi" yang unik dari citra-Nya, dari asma-asma-Nya, yang mengindikasikan suatu urusan yang Allah hendak wakilkan kepada masing-masing kita demi memakmurkan Bumi ini.
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّـهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” – Q.S. Huud [11]: 61
Maka, mari renungkan dalam-dalam tentang penciptaan manusia ini, penciptaan diri kita semua, para saksi Allah, yang berperan sebagai abdi-Nya, ksatria-Nya dalam mengemban suatu tugas atau misi suci tertentu dari Allah Ta’ala. Kita, yang dilengkapi sekian khazanah ilahiah yang disematkan ke dalam relung diri (nafs/jiwa) kita yang terdalam, sebagai wakil-Nya untuk sebuah urusan suci di muka bumi ini.
Ya, masing-masing kita.
Tiap-tiap diri bekerja sesuai dengan untuk apa dia diciptakan, atau menurut apa yang dimudahkan kepadanya. – H.R. Bukhari