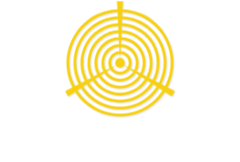APA itu thariqah? Bagaimana hubungannya dengan agama Islam? Apakah ber-thariqah diajarkan oleh Rasulullah SAW?
Thariqah adalah bahtera untuk mengarungi samudera kehidupan—sebuah cara untuk menempuh lautan dunia tanpa tenggelam atau terbasahi oleh keduniawian—dengan bahtera yang dibangun berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah
Kata thariqah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “jalan”, setara dengan kata “path” atau “way” dalam bahasa Inggris. Thariqah, atau “tarekat”, dalam konteks agama Islam, berarti jalan pertaubatan untuk kembali kepada Allah (“taubat” berasal dari kata “taaba” yang artinya “kembali”), melalui jalan penyucian jiwa dan penyucian hati.
Di sisi lain, meski kata syariat juga memiliki makna “jalan”, yang setara dengan “road” atau “street” dalam bahasa Inggris, makna thariqah adalah jalan yang lebih abstrak, lebih halus, dan mutlak membutuhkan petunjuk arah untuk menempuhnya. Jalan “syariat” adalah jalan seperti di kota atau di daratan: seseorang cukup melihat sekelilingnya untuk mengetahui posisi dan ke arah mana ia harus melangkah. Sedangkan jalan “thariqah” adalah jalan yang tak terlihat seperti di lautan atau di padang pasir: untuk mengetahui posisi dan arah, seseorang harus melihat dan memahami posisi bintang, matahari, mencermati arah angin, burung, hewan dan sebagainya, alih-alih sekedar melihat ke sekeliling. Di jalan yang tak tampak seperti ini, rasa pengharapan dan kebutuhan pertolongan Yang Maha Kuasa akan muncul sangat nyata pada diri seseorang.
Dalam Al-Qur’an, kata thariqah dikaitkan dengan makna literal maupun makna simbolik. Sebagai contoh, perintah Allah untuk tetap istiqomah di atas thariqah agar dianugerahi air yang berlimpah (sebagai simbol keberlimpahan ilmu pengetahuan), pada Q.S. Al-Jin [72]: 16,
وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا
Dan sekiranya mereka mengokohkan diri di atas thariqah, sungguh Kami akan benar-benar memberikan pada mereka air yang menyegarkan. – Q.S. Al-Jin [72]: 16
atau pada Q.S. Thaahaa [20]: 77,
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ
Dan sungguh, telah Kami wahyukan pada Musa, ‘Tempuhlah perjalanan di malam hari bersama para hamba-hamba-Ku, buatlah untuk mereka jalan kering di laut (thariqan fil bahr). Janganlah mencemaskan akan tersusul, dan janganlah menjadi takut. – Q.S. Thaahaa [20]: 77
Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan kata “thariqah” sebagai simbol perintah agar manusia menjalani kehidupannya di dunia dengan membuat jalan kering di laut: yaitu mengarungi lautan kehidupan duniawi tanpa terbasahi atau tenggelam di dalamnya. Dalam makna yang lebih dalam, Allah menjadikan sejarah Nabi Musa a.s. sebagai perlambang: Musa melambangkan jiwa kita yang telah mendapatkan pertolongan dan penguatan dari Allah, kaum Bani Israil melambangkan hawa nafsu diri kita, dan pembebasan seluruh Bani Israil dari perbudakan di negeri Mesir melambangkan pembebasan hawa nafsu dan syahwat kita dari perbudakan di negeri jasadiah menuju ke tanah yang dijanjikan.
Itulah esensi dari sebuah thariqah yang haqq. Pertama, sebagai sebuah metode untuk menempuh jalan taubat—jalan untuk kembali kepada Allah—yaitu untuk meraih ampunan Allah, untuk memperoleh pengajaran-Nya mengenai siapa diri kita ini sebenarnya dan apa esensi kehidupan ini, bagaimana memahami agama dan hakikatnya, serta bagaimana agama Rasulullah Muhammad SAW bisa menjadi jalan untuk memperoleh semua itu. Kedua, sebagai sebuah metode untuk “menempuh jalan kering di laut”: cara untuk menempuh kehidupan di dunia tanpa ditenggelamkan oleh hasrat jasadiah maupun keduniawian.
Memahami Kehidupan, Memahami Agama
Salah satu natur alamiah manusia adalah kebutuhan untuk memahami sesuatu hingga ke esensinya. Demikian pula dalam upaya manusia memahami diri, dunianya, dan agamanya. Dan semakin kita mendalami agama, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan sisi batin agama.
Dalam menyelami agama, semakin lama kita akan semakin membutuhkan pemahaman yang lebih presisi tentang hal-hal tertentu. Dan natur kita, manusia, pada akhirnya tidak akan terpuaskan lagi dengan hal-hal yang sifatnya pemahaman tekstual saja, atau mengasosiasikan satu bangunan besar Ad-Diin yang utuh lahir batinnya semata-mata hanya sebagai hafalan dalil-dalil. Di titik ini, manusia membutuhkan makna, sesuatu yang lebih hakiki untuk dipahami, baik dari agama maupun dari kehidupannya sendiri.
Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, seperti apa hidup itu sebenarnya, mengapa Al-Qur’an tidak mudah dipahami strukturnya maupun esensinya, apa beda iman dan takwa, apa makna presisi dari “yaumid-Diin” (hari Ad-Diin), apa makna “ulil albab”, apa beda “amal” dan “amal shalih”, untuk apa amal jika Allah telah memiliki ketetapan atas segala hal, dan apa maksud Rasulullah SAW yang menjawab dengan “sesungguhnya manusia diciptakan untuk apa-apa yang dimudahkan baginya”, ketika para sahabatnya yang mulia bertanya tentang untuk apa sebenarnya manusia beramal—ini adalah contoh-contoh persoalan yang harus terpahami hingga ke hati, dengan pemahaman yang presisi.
Dalam pemahaman yang lebih hakiki, Ad-Diin tidak bisa terpisahkan dari takdir kehidupan kita masing-masing. Baik Ad-Diin, Al-Qur’an, kehidupan ini maupun diri kita, masing-masing adalah sebuah kitab dari Allah Ta’ala yang harus dibuka dan dipahami. Oleh karena itu, untuk memahami diri dan kehidupan adalah dengan memahami Ad-Diin, dan demikian pula sebaliknya.

Ad-Diin tidak bisa terpisahkan dari takdir kehidupan kita masing-masing. Baik Ad-Diin, Al-Quran, kehidupan ini maupun diri kita, masing-masing adalah sebuah kitab dari Allah Ta’ala yang harus dibuka dan dipahami.
Esensi Agama
Berbeda dengan asumsi umum bahwa pertimbangan paling dasar dalam agama adalah dalil-dalil hukum syariat, semakin lama kita akan menyadari bahwa ada pertimbangan yang lebih mendasar daripada sekedar hukum-hukum syariat. Dengan kata lain, titik tolak perilaku yang dianggap “baik” dalam agama bukan saja yang sesuai dengan hukum fikih dan syariat saja, namun bahkan ada yang lebih mendasar dari itu.
Sebagai contoh: aurat pria. Batasan aurat bagi pria adalah semua bagian tubuh antara pusar hingga lutut. Itu wajib ditutup terhadap semua orang yang bukan mahramnya.
Lalu, syarat sah shalat adalah menutup aurat. Secara fikih, jika shalat hanya mengenakan celana dari pusar sampai lutut dan tak mengenakan baju atasan, maka shalat tersebut sah. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat hal ini.
Kemudian, dia pergi ke masjid, lalu menjadi imam shalat di sana—dengan pakaian yang sama: celana selutut dan tanpa baju atasan. Sahkah shalat berjamaah tersebut? Sah, jika hanya fikih, atau syariat lahiriah, yang jadi pertimbangannya.
Tapi maukah Anda menjadi ma’mumnya? Anda akan marah, menganggapnya lancang, dan merasa terhina dengan cara imam berpakaian ketika menjadi imam shalat.
Sah, secara fikih. Tapi bagaimana mungkin seseorang menghadap Allah Ta'ala atau menjadi imam dengan pakaian seperti itu? Apakah Allah Ta’ala berkenan? Apakah ia telah menghargai Allah Ta’ala maupun seluruh jamaah dengan sikap seperti itu, atau ia hanya mempermainkan hukum saja?
Atau, seorang anak lelaki sah secara hukum syariat, jika dia menikah tanpa memberi tahu orangtuanya sama sekali. Namun, apakah ia telah menghargai ayah ibunya—yang telah bersusah payah membesarkannya— dengan bersikap seperti itu?
Agama harus dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik itu aspek lahir maupun aspek batin, baik itu syariat dan hukum fikih maupun adab, rasa, niat, ketulusan hati dan kesempurnaan perilaku di mata Allah Ta’ala. Agama tidak akan utuh sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam-alam, jika diidentikkan atau hanya memfokuskan salah satu aspeknya saja.

Agama harus dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik itu aspek lahir maupun aspek batin, baik itu syariat dan hukum fikih maupun adab, rasa, niat, ketulusan hati dan kesempurnaan perilaku di mata Allah Ta’ala.
Ad-Diin sesungguhnya bukan hanya ritual, mazhab, sederetan dalil, atau hukum syariat saja. Ad-Diin sesungguhnya jauh, jauh lebih besar dan jauh lebih dalam dari itu.
Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Rabb-mu. – H.R. Al-Baihaqi
Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan memperindahnya kecuali ada satu labinah (tempat lubang batu bata yang belum terselesaikan) yang berada di dinding samping rumah tersebut, lalu manusia mengelilinginya dan terkagum-kagum sambil berkata: 'Duh, seandainya ada orang yang meletakkan labinah (batu bata) di tempatnya ini'. Beliau bersabda, 'Maka, aku lah labinah itu dan aku adalah penutup para nabi.' – H.R. Bukhari, Muslim
Tiga Sisi Agama
Agama, atau Ad-Diin, sesungguhnya terdiri dari tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain: Islam, Iman dan Ihsan sebagaimana yang termaktub di sebuah hadits [1]. “Islam” terkait dengan ibadah formal, hukum syariat dan fikih. ”Iman” terkait dengan cahaya iman, akidah, tauhid dan keyakinan. “Ihsan” terkait dengan kesempurnaan islam dan iman-nya, sejauh mana seseorang melihat Allah dalam perilakunya, atau dilihat Allah dalam perilakunya, sehingga perbuatannya akan dijaga sesempurna mungkin, baik dari sisi lahir atau batinnya.
Aspek “ihsan” inilah yang jauh lebih dalam dari sekadar syariat, yang memagari seseorang untuk shalat sekenanya dengan bertelanjang dada dan bercelana selutut, meski secara hukum syariat perbuatan itu sah. Atau, mencegah seseorang merasa dengki, meremehkan orang, jatuh cinta dengan pasangan orang lain, atau bangga diri dan merasa sombong jauh di dalam hati, walaupun hukum syariat belum bisa menyentuh atau menghukumi perilaku batinnya itu. Sementara, sudah merupakan perintah yang sangat jelas bahwa kita diharuskan untuk tidak melakukan dosa, baik dosa lahiriah maupun dosa batiniah.
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
Dan tinggalkanlah dosa yang dzahir dan yang batin. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan dibalas, disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. – Q.S. Al-An’aam [6]: 120
Dalam agama, wilayah ini disebut “syariat batiniah”. Ini adalah aspek penimbang lain yang lebih dalam dari sekadar hukum lahiriah, yang kadang hukum kedua ini tidak bisa dirumuskan. Ada aspek rasa, adab, dan kepatutan yang sangat dominan di sini: sejauh mana Allah akan suka pada perbuatan lahir maupun rasa batin seseorang. Tataran ini lebih dalam dari tataran syariat, sebab walaupun hukum syariat belum mampu menyentuh lintasan-lintasan batin, namun apapun yang terjadi dalam batin kita kelak tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta’ala.
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًاٰ
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. – Q.S. Al-Israa’ [17]: 36
Pada awalnya, di masa Rasulullah, ketiga aspek agama ini menyatu, utuh, tidak terpisah-pisah dalam satu label yang dibawa Beliau SAW: Diin Al-Islam; agama keberserahdirian pada Allah. Inilah sebabnya tidak ada istilah sufisme atau tasawuf di masa Beliau SAW, karena aspek ihsan yang kerap diasosiasikan dengan tasawuf ini sudah menjadi bagian yang utuh dari Diin Al-Islam.

Lama kelamaan, karena terkait studi, budaya dan kepentingan politik, ketiga aspek ini terpisah satu sama lain. Sayangnya, kebanyakan penganutnya semakin lupa bahwa Diin Al-Islam tadinya terdiri dari tiga aspek yang menyatu utuh. Belakangan, di usia-usia termuda peradaban, muncul gerakan yang pada awalnya ingin memurnikan agama Islam dari segala bentuk kemungkinan bid’ah dan khurafat, namun berkeras bahwa hanya aspek “Islam” sajalah yang merupakan bagian dari agama Islam. Aspek “Iman” direduksi menjadi hanya sebuah implikasi dari pengucapan ikrar dua kalimat syahadat, dan aspek “ihsan”, dikeluarkan dari bangunan Ad-Diin yang utuh, dan dilabeli dengan tasawuf atau sufisme, dan dianggap bukan dari ajaran Rasulullah.

Thariqah, adalah bagian dari sisi iman dan ihsan dari seluruh bangunan Ad-Diin. Thariqah adalah jalan, atau metode, untuk memahami esensi-esensi, berbagai hakikat dari agama. Dan, karena Ad-Diin tidak bisa dipisahkan dari takdir kehidupan masing-masing yang sedang dijalani, maka thariqah pun menjadi jalan untuk memahami hakikat kehidupan.
Pada akhirnya, jalan pulang kepada Allah (taubat) ini pun menjadi jalan untuk mengenali secara hakiki siapa diri kita masing-masing, kenapa dan untuk apa kita dianugerahi sebuah eksistensi, dan memahami dengan sungguh-sungguh betapa berharganya nilai kita di mata Allah Ta’ala.
Melangkah masuk ke dalam wilayah esensi agama untuk meraih pemahaman mendasar, atau melangkah di atas jalan thariqah, sesungguhnya merupakan sebuah implikasi logis bagi siapa pun yang ingin memahami Ad-Diin Al-Islam, kehidupan masing-masing, atau diri sendiri—dengan lebih mendalam dan lebih hakiki. Melalui thariqah seseorang berangkat dari wilayah “ritual agama” ke wilayah “pelaksanaan ritual agama dengan fondasi pemahaman hakiki”.
Catatan Kaki:
1. Hadits yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:
Dari Umar r.a.: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya.
Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW seraya berkata: "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam", maka bersabdalah Rasulullah SAW: "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan pergi haji jika mampu", kemudian dia berkata: "Engkau benar." Kami semua heran, dia yang bertanya namun dia pula yang membenarkan.
Kemudian orang itu bertanya lagi: "Beritahukan aku tentang Iman". Lalu Beliau SAW bersabda: "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk", kemudian dia berkata: "Engkau benar."
Kemudian dia berkata lagi: "Beritahukan aku tentang Ihsan." Lalu Beliau SAW bersabda: "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau."
Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau SAW bersabda: "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan Agama kalian“.
– H.R. Muslim